Spiritualitas Pendidikan
 “Aku
berpikir, maka aku ada.” Sejak Bapak Filsafat Modern Rene Descartes
(1596-1650) mengemukakan ungkapan itu, “berpikir” menjadi begitu penting
di dunia. Paradigma analitis logis Cartesian, paham yang didasarkan
pada pandangan Descartes, dengan segera menggusur cara pandang holistik
Ibnu Sina (980-1037) yang mendominasi global selama enam abad.
“Aku
berpikir, maka aku ada.” Sejak Bapak Filsafat Modern Rene Descartes
(1596-1650) mengemukakan ungkapan itu, “berpikir” menjadi begitu penting
di dunia. Paradigma analitis logis Cartesian, paham yang didasarkan
pada pandangan Descartes, dengan segera menggusur cara pandang holistik
Ibnu Sina (980-1037) yang mendominasi global selama enam abad.
Dunia menyambut paradigma baru itu.
Diperkuat oleh temuan Newton (1643-1727) tentang hukum gravitasi, paham
Cartesian pun menguasai seluruh sendi kehidupan. Hasilnya, Barat melesat
dalam peradaban dunia berbasis materialistik. Penjajahan dengan
penjarahan pada bangsa lain di satu sisi, dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi di sisi lain menjadi kunci kemajuannya.Paham
analitis logis Cartesian pun terus berkembang, termasuk ke dunia
pendidikan. Taksonomi Bloom yang menjadi acuan penting pendidikan pun
diterjemahkan secara Cartesian. Menurut Bloom, ranah pendidikan adalah
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Implementasinya menjadi kognitif,
kognitif, kognitif. “Berpikir, berpikir, berpikir.” Terutama di
Indonesia.
Pilihan itu dapat dimengerti. Kognitif
atau “berpikir” adalah ranah yang paling mudah diukur. Dianggap ilmiah
hanya bila dapat diukur. Ujian nasional adalah produk cara pandang itu.
Begitu pula kurikulum pendidikan selama ini. Menjejalkan pengetahuan
lalu mengujinya dianggap sebagai hal semestinya dalam pendidikan.
Dalihnya: “Pendidikan kan ranah ilmiah. Harus serbaterukur.”
Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara
pernah mencoba melawan arus tersebut. Ia mengusung pendekatan holistik
ketimuran. Ungkapan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut
wuri handayani merupakan produk cara pandang itu. Kalangan pendidikan
Indonesia mengapresiasi dan mengutip ucapannya, tapi diam-diam lebih
mengadopsi paham Cartesian.
Alasannya sederhana. Kognitif, sekali
lagi, paling mudah diukur. Selain itu, buku-buku teks Barat tersedia
melimpah untuk dijadikan buku teks babon. Tak ada buku teks babon
berbasis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemerintah pun tak tertarik
mengembangkannya, sebagaimana para universitas negeri (mantan IKIP) juga
tak tertarik pendekatan kualitatif karena dianggap “kurang ilmiah”.
Dengan paradigma seperti itu,
pendidikan nasional pun kering dan jauh dari efektif. Apalagi dengan
administrasi birokrasi yang telanjur biasa bekerja dengan sistem ad hoc.
Belum lagi penurunan kualitas SDM pendidikan setelah putra-putra
terbaik bangsa lebih banyak diserap sektor lain. Sebagian besar mereka
hanya mampu mengajar. Bukan mendidik. Itu pun secara pas-pasan.
Maka, pendidikan nasional pun terus
mengajarkan pengetahuan atau “berpikir”. Bukan mendidik. Hal yang
diharapkan membuat siswa cerdas, tapi membuat hasil sebaliknya. Menurut
penilaian program internasional PISA, daya nalar siswa Indonesia
termasuk terendah dibanding bangsa lain. Wajar bila Menteri Anies
Baswedan menyebut dunia pendidikan Indonesia sudah gawat darurat.
Menekankan “berpikir” terbukti tak
membuat siswa pandai berpikir. Sebaliknya malah membuat mereka tidak
cakap hidup. Agar berkecakapan hidup, siswa perlu pendidikan yang
dislogankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri. Yakni
pendidikan berupa “olah hati, olah pikir, olah raga (olah
fisikal-mental), serta olah rasa dan karsa (olah emosi-sosial)”.
Sayangnya, empat “olah” itu juga tak
menjadi buku teks babon pendidikan. Jadilah olah pikir lagi, olah pikir
lagi. Polemik kurikulum sekarang merupakan produk budaya olah pikir itu.
Kecenderungan yang hendak dipatahkan dengan Kurikulum 2013, dan
ternyata gagal. Selain karena kurikulum—hasil kerja ad hoc—Itu tak cukup
memadai, juga karena paham olah pikir masih begitu dominan.
Kini saatnya mengubah pendidikan yang
menekankan “berpikir”. Kini saatnya untuk membangun pendidikan yang
sungguh-sungguh memberdayakan. Untuk itu spiritualitas pendidikan
diperlukan. Dengan spiritualitas pendidikan, aspek kultural-spiritual
dikedepankan. Keteladanan dan pembiasaan pun didahulukan dibanding
pengajaran. Pengajar perlu ditransformasi menjadi pendidik.
Dengan spiritualitas pendidikan, olah
hati menjadi yang pertama. Baru kemudian diikuti dengan olah pikir, olah
raga, serta olah rasa dan karsa. Bukan lagi “mengajari”, melainkan
“menyayangi” yang menjadi kata kuncinya. Bukan lagi kuantitatif
melainkan kualitatif yang menjadi alat ukurnya. Itu yang akan membuat
siswa berdaya. Terutama setelah cara pandang “aku berpikir, maka aku
ada” tergantikan oleh “aku sayang, maka aku ada”.
Zaim Uchrowi ; Guru Karakter dan Transformasi KULTURA Leadership
REPUBLIKA, 15 Desember 2014
Category: Artikel Pendidikan, Artikel Umum, Sekolah









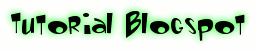
0 komentar